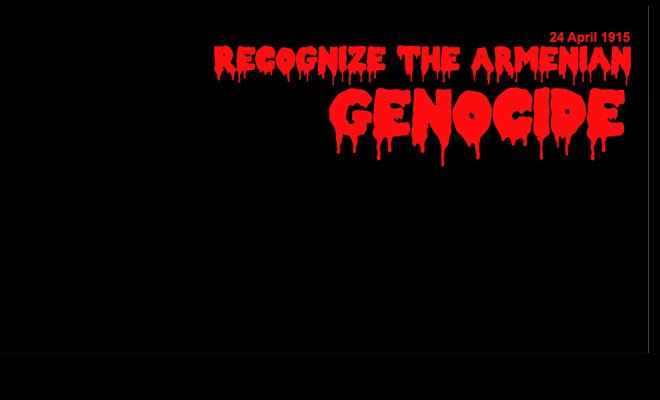“Tuhan adalah Ketiadaan sepenuhnya
Tak tersentuh Waktu dan Tempat:
Semakin kau tangkap Dia
Semakin ia lepas dari jerat?”
Angelus Silesius, seorang penyair cum mistikus asal salah satu daerah pedalaman Jerman menulis potongan puisi diatas. Angelus mengungkapkan bahwa dunia adalah bentuk kenihilan yang lain melalui puisinya. Nampaknya saat puisi itu ditulis, ia berpijak dari pengalamannya bertemu para pengungsi atas nama perbedaan iman. Seperti yang belakangan ini terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika agama dipersempit, lantas menimbulkan sebuah aforisme yang disebut ‘kebencian’. Kebahagiaan berubah jadi bengis. Frasa ‘kesatuan’ pun luntur. Bahkan nihil.
Mungkin Angelus juga tak lepas dari situasi perang antara kaum Protestan dan kaum Katolik yang berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Beberapa kemungkinan diciptakan agar perdamaian terjadi. Namun perang yang didasari perbedaan iman itu terus berlanjut dan semakin parah. Konflik atas dasar kepercayaan pun tak bisa lepas. Banyak darah, kesakitan, kepiluan, dan tentu kehilangan. Sejarah tentu mencatatnya sebagai sebuah refleksi agar tak ada lagi dendam ketika semua konflik itu berakhir.
Indonesia dengan julukan Negara Seribu Pulau, tentu memiliki banyak keberagaman. Baik dari segi suku, kepercayaan, budaya, bahkan yang paling kecil adalah warna kulit. Barangkali atas dasar itulah Bhineka Tunggal Ika dikukuhkan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mewujudkan konsep ‘bernegara’.
Keberagaman lah yang membuat Indonesia menjadi negara yang kuat. Seperti yang diungkapkan Bennedict Anderson lewat Imagined Community, yaitu sesuatu yang melebur menjadi satu tapi tetap memiliki sifat majemuk. Sifat majemuk inilah yang harusnya dijaga oleh Indonesia sebagai salah satu kekayaan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain.
Tapi fakta yang lahir dewasa ini sangat berbeda, perbedaan dianggap sebagai pengusik yang harus segera dilebur. Minoritas harus dihancurkan dan mayoritas semakin merdeka. Konflik atas dasar segala perbedaan pun muncul, atau barangkali sengaja dimunculkan. Pemerintah kesulitan mengambil peran, mereka tersentak lalu hanya terdiam. Apa yang disebut Anderson sebagai Imagined Community semakin tipis dan kepentingan mayoritas semakin diagungkan. Lalu mau dibawa kemana kemerdekaan yang dibentuk atas nama keberagaman?
Konflik Atas Nama Perbedaan Keyakinan
Mungkin yang paling lekat dalam ingatan adalah konflik agama di Indonesia yang sampai sekarang belum juga terselesaikan. Kita ingat Ahmadiyah, Syuni-Syiah, dan yang paling rasial menurut saya adalah pengucilan masyarakat yang mempunyai kepercayaan kedaerahan. Tapi apakah masyarakat minoritas itu mendapatkan hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia?
Ahmadiyah adalah kaum minoritas yang dianggap menistakan islam. Tapi apakah mereka benar-benar menistaan agama islam? Apakah dengan dikucilkan permasalahan akan selesai? Barangkali jawabannya adalah ‘tidak’. Pengucilan jamaat ahmadiyah malah akan memunculkan kemungkinan mereka menyimpan dendam dan para penganutnya akan cenderung menyembunyikan identitas mereka sebagai jamaat ahmadiyah. Kemungkinan yang lain adalah para jemaat ahmadiyah akan kesulitan berkomunikasi dengan kelompok lain diluar kelompok mereka, walaupun kelompok lain itu tidak menganggap mereka menyimpang.
Manusia sebagai subjek yang penuh sadar akan dunia akan selalu mempunyai keinginan untuk membentuk sebuah kebahagiaan tunggal bagi dirinya. Tapi seperti yang disebutkan oleh Daniel Dhakidae dalam pengantar buku Imagined Community, Indonesia dalam sumpah pemuda dibentuk sebagai The Holy Trinity atau tritunggal suci yaitu bahasa, bangsa dan tanah air. Dari situ terlihat bahwa Indonesia bukanlah kelompok yang intoleran. Bagaimana kesepakatan sumpah pemuda menjadikan Indonesia yang beragam menjadi satu demi kebaikan berkehidupan dengan berbagai perbedaan dan pertimbangan yang matang.
Tapi semakin kesini perbedaan tampak sebagai yang banal dan mengancam. Beberapa kelompok yang berkepentingan dengan mudah membelokkan norma dan menjadikan gagasan mereka menjadi sesuatu yang universal, yang harus di amini oleh semua orang. Tapi gagasan yang universal menurut Derrida, tidak selamanya harus menyingkirkan yang partikular. Maka kepercayaan lokal—yang tertanam turun temurun, adalah yang partikular. Disinilah nilai keberagaman lahir dan harus dihargai.
Seperti halnya agama di Indonesia, kelompok agama mayoritas seperti ingin menghilangkan yang partikular. Tapi bukankah Tuhan adalah Ketiadaan sepenuhnya dan Tak tersentuh Waktu dan Tempat. Setiap manusia punya hasrat dan kerinduan spiritual yang berbeda dan tak terbahasakan kepada illah. Sempat ketika saya sedang nongkrong di warung kopi bersama salah seorang teman, ada beberapa pemuda yang sedang membicarakan tentang konflik Syiah-Sunni di Sampang. Salah seorang dari mereka berbicara tentang bagaimana kelompok Syiah beribadah tanpa menghadap Ka’bah dan menganggap hal itu merupakan sebuah penyimpangan.
Lantas seperti apa yang tidak menyimpang? Kalimat itu yang langsung muncul dalam pikiran saya ketika mendengar obrolan beberapa pemuda itu. Dari beberapa sudut pandang, adakah kebenaran tunggal? Bukankah perbedaan itu wajar ketika ada beberapa sudut pandang? Apakah ada sudut pandang lain yang harus dikoyak. Dimarjinalkan? Lantas dimana lagi keberagaman harus dijunjung?
Ada lima agama yang diakui oleh kementrian agama di Indonesia, tapi apakah kepercayaan-kepercayaan lain di luar lima agama itu harus dikesampingkan atau dihapuskan? Ada banyak sekali kepercayaan lain di luar agama yang belum diakui oleh negara. Bahkan di setiap pulau mempunyai kepercayaan tradisionalnya masing-masing, yang bersifat taken for granted dari pendahulu mereka.
Saya jadi teringat salah satu kalimat yang diucapkan oleh Derrida, “je ne sais pas, il faut croire”. Dalam kalimat itu derida mengungkapkan bahwa iman tak bisa dibahasakan atau dilihat secara umum. Iman hanya ada di dalam diri masing masing individu sebagai the wholly other yang tidak terterjemahkan. Bahkan melampaui pengetahuan.
Tapi sayangnya di Indonesia otoritas beragama dan berkeyakinan masih didominasi oleh aparatur negara. Bukan dipegang oleh individu-individu yang mempunyai imannya masing-masing. Barangkali Indonesia masih terjebak dalam zaman kosong sebelum renaissan di eropa dulu. Pada zaman itu gereja punya otoritas penuh atas apa yang dilakukan oleh para penduduknya. Gereja dianggap perlambangan tuhan yang bisa mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tapi sepertinya yang terjadi di Indonesia sekarang lebih lunak atau bisa jadi lebih jahat. Kenapa saya mengatakan bisa jadi lebih jahat, karena sudah banyak konflik atas nama perbedaan kepercayaan yang dipenuhi darah, bahkan sampai merenggut nyawa manusia.
Sebuah Tawaran Baru Beragama
Barangkali ada sentimen besar, yang memicu terjadinya berbagai konflik agama di Indonesia. Atau mungkin juga konflik itu dipicu oleh kepentingan kelompok tertentu. Yang pasti saya belum bisa menjawabnya. Tapi Al-Fayyadl mungkin sudah bisa dibilang menemukan jawaban tentang sentimen yang timbul di Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Derrida, Fayyadl menuliskan tentang ‘agama tanpa-agama’ yang dipikirkan oleh Derrida. ‘Agama tanpa-agama’ menurut Derrida ini tentunya bukan agama dalam pengertian yang harfiah dan konvensional.
Seperti yang ditulis oleh Fayyadl, ‘agama tanpa-agama’ tidak menafikan hadirnya institusi agama yang sudah ada dan sudah membuat sejarah, dalam hal ini Indonesia punya Kemnetrian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). ‘Agama tanpa-agama’ lebih merupakan undangan menuju keberagaman baru dan bagaimana mencapai yang Illah dengan ketidakmungkinan yang berbeda-beda. ‘Agama tanpa-agama’ hanya ingin membebaskan pengalaman religius kita dari keterbatasan yang dibentuk oleh tradisi atau institusi agama, karena menurut Derrida tak ada iman yang selesai. Iman akan selalu berproses tanpa ada akhirnya.
Indonesia sebagai negara yang dibentuk dari keberagaman tentu seharusnya memberikan kebebasan terhadap pengalaman religius warganya dan menjaga agar tidak ada lagi konflik atas nama perbedaan. Keberagaman, entah itu dalam aspek kepercayaan dan budaya memang harus dijaga. Agar kalimat yang dicengkram burung garuda sebagai lambang negara Indonesia tidak ternoda. Dalam hal ini tanggung jawab yang besar ada pada pemerintahan Indonesia.
Saya kira warga Indonesia sangat mencintai keberagaman beragama dan dalam keberagaman menurut saya tidak akan ada kebenaran tunggal. Seperti yang ditulis Angelus bahwa Semakin kau tangkap Dia sebagai Tuhan atau kepercayaan, maka Semakin ia lepas dari jerat?, semakin kita tidak akan menemukan titik temu keberagaman. Maka jika saya ditanya apa agama saya, maka saya akan menjawab: “Agama saya adalah keberagaman.”[]